Buya Berhati Lapang

i-life.id--- “Karena kau adalah ulama, Malik, bukan orang politik. Ulama tak boleh berdekat-dekat dengan penguasa, apalagi penguasa yang penjajah. Itu menyakiti perasaan rakyat.” — Serangkai Makna di Mihrab Ulama, hlm. 54
Peringatan itu diberikan kepada Buya Hamka oleh ayahnya ketika beliau—sebagai konsul Muhammadiyah Sumatra Timur—memilih untuk berkolaborasi dengan Jepang.
Itu cuplikan dari novel sejarah-biografi yang ditulis dengan menarik sekali oleh Akmal Nasery Basral mengenai kehidupan salah seorang pahlawan nasional, Buya Hamka.
Buku ini adalah buku kedua dari dwilogi, menuturkan kisah sepak terjang sang ulama-pujangga dari umur 31 tahun hingga wafatnya pada tahun 1981. Pada kurun waktu itu, terjadi paling tidak lima babak sejarah di Indonesia, mulai dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa perjuangan kemerdekaan, masa pemerintahan orde lama, dan masa orde baru. Bagaimana peran Hamka di setiap babak itu dituturkan penulis dengan referensi yang jelas. Sehingga, dengan membaca buku ini, kita seperti sedang membaca sejarah Indonesia yang dituturkan dengan bahasa yang renyah, bahasa novel. Dan, kita lebih mudah memahaminya.
Bahkan, penulis justru mengemukakan berbagai informasi yang, paling tidak bagi saya, sulit didapatkan dari sumber lain. Di antaranya adalah, bahwa kaum komunis di Indonesia juga pernah melakukan pemberontakan di Silungkang, Sumatra Barat, pada 1 Januari 1927 (hlm. 12-16). Yang menarik juga adalah informasi yang dikemukakan oleh Hamka mengenai alasannya tidak bersedia untuk hadir pada acara penyambutan kenegaraan kunjungan Paus Paulus VI ke Indonesia pada tahun 1970 (hlm. 233-234).
Namun, yang membuat novel ini menjadi sangat menarik adalah cukilan-cukilan kehidupan pribadi buya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang kakek. Bagaimana, dalam kehidupannya yang super-sibuk, dia masih punya waktu mengajarkan pada cucunya bagaimana memakan pangek ikan bandeng tanpa terganggu oleh durinya (hlm. 300). Bagaimana kerendah-hatian buya serta kemampuan silatnya dituturkan dengan manis pada sebuah peristiwa ketika buya dan anaknya pulang dari satu kegiatan di Bandung memilih baik bus umum, dan ketika istirahat untuk sholat di sebuah mushala, mereka diancam tiga berandal dengan pisau untuk merampas dompet buya. Tapi apa yang terjadi? Dalam usia yang sudah cukup tua itu, dengan kesigapan seorang pesilat kawakan, sang berandal malah sudah ditaklukkan buya dalam sekejap mata (hlm. 127-128)
Hamka juga adalah tokoh yang berhati lapang dan berjiwa besar. Meskipun dia pernah dipenjarakan Soekarno, ketika sang proklamator itu wafat, dia bersedia memenuhi permintaan Soekarno untuk mengimami sholat jenazahnya. Meskipun Muhammad Yamin bermusuhan dengannya, namun buya tetap bersedia mendampingi Yamin menghadapi saat-saat ajalnya dan setelah meninggal dunia mengantarkannya ke Talawi, Sumatra Barat untuk dimakamkan sesuai dengan permintaan almarhum.
Bahkan, ‘musuh besar’-nya dalam dunia sastra, Pramudya Ananta Toer, ketika anaknya akan menikah, minta buya Hamka yang membimbing calon suaminya menjadi mualaf. Dan, buya memenuhinya.
Sungguh, ini adalah novel biografi yang sekaligus novel sejarah yang sangat saya rekomendasikan untuk dibaca sekarang ini.
Medan, 14 April 2022
Prof. Dr. Ir. Darwin S. Sitompul, M.Eng (USU, Medan)






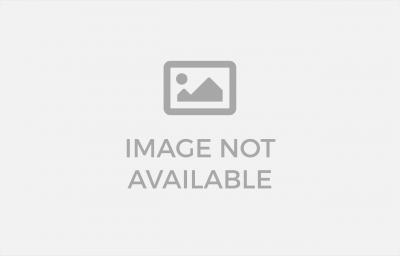 Kabar Pesantren
- 13 Mar 2025
Kabar Pesantren
- 13 Mar 2025

